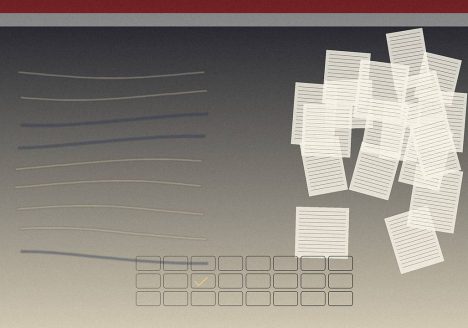Bayangkan jika kita punya tombol darurat untuk memecat anggota DPR yang malas, korup, atau tak lagi mewakili suara rakyat—tanpa menunggu lima tahun sekali. Di Venezuela, tombol itu ada dan kita bisa belajar dari negara dengan sistem proporsional dan sistem distrik itu. Sejak 1999, Konstitusi Bolivarian memberi rakyat hak untuk mencabut mandat pejabat terpilih, termasuk anggota parlemen (Asamblea Nacional), lewat mekanisme recall referendum (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Pasal 72).
Aturannya sederhana di atas kertas: setelah melewati setengah masa jabatan, seorang pejabat bisa ditantang lewat petisi rakyat. Jika 20 persen pemilih terdaftar menandatangani petisi, maka referendum digelar. Agar sah, jumlah suara “YA” harus setidaknya sama dengan suara yang dulu memilihnya, dengan tingkat partisipasi minimal 25 persen pemilih.
Praktiknya, tentu tak sesederhana itu. Otoritas pemilu Venezuela, Consejo Nacional Electoral (CNE), kerap menambah syarat administratif. Pada upaya recall 2016, misalnya, oposisi diwajibkan lebih dulu mengumpulkan tanda tangan 1 persen pemilih di tiap negara bagian sebelum bisa melangkah ke tahap 20 persen penuh (Reuters, 1 Agustus 2016; Venezuelanalysis, 2 Agustus 2016). Mahkamah Agung (TSJ) bahkan mempersempit peluang dengan putusan Oktober 2016 yang mewajibkan tanda tangan 20 persen itu terkumpul di setiap negara bagian, bukan hanya secara nasional (Reuters, 20 Oktober 2016; TSJ, 18 Oktober 2016). Dengan cara itu, peluang referendum praktis dipasung.
Contoh paling dramatis adalah referendum recall Presiden Hugo Chávez pada 2004. Oposisi berhasil mengumpulkan tanda tangan, tapi hasil akhirnya mengejutkan: 59 persen pemilih justru menolak recall, membuat Chávez kian kuat (The Carter Center, 2005). Dua belas tahun kemudian, upaya serupa terhadap Nicolás Maduro kandas di meja birokrasi dan peradilan.
Lebih menyeramkan lagi, ada efek jera dari politik daftar hitam. Setelah referendum 2004, publik dikejutkan dengan munculnya “Daftar Tascón,” yang memuat lebih dari 2,4 juta nama warga penandatangan recall (Wikipedia, “Lista Tascón,” diakses 1 September 2025). Daftar itu dipakai untuk mendiskriminasi warga oposisi, dari pemecatan pegawai negeri hingga penolakan lamaran kerja. Human Rights Watch mencatat kasus puluhan hingga ratusan pegawai publik yang kehilangan pekerjaan atau dimutasi karena dianggap pro-recall (HRW, 2008; HRW, 2016). Maka tak heran, banyak warga enggan menandatangani petisi, takut hidupnya hancur hanya karena bersuara.
Di atas kertas, recall referendum adalah senjata rakyat untuk menundukkan politisi yang bandel. Tapi Venezuela menunjukkan sisi gelapnya: tanpa lembaga independen, mekanisme demokrasi justru jadi alat represi atau sekadar panggung manipulasi.
Pelajarannya jelas: demokrasi bukan cuma soal memilih, tapi juga soal mencabut pilihan. Indonesia bisa saja belajar dari Venezuela untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Tetapi kita juga harus sadar: aturan di atas kertas tak ada artinya tanpa penegakan hukum yang adil dan keberanian melindungi hak-hak sipil. Tanpa itu, “tombol darurat” bisa berubah jadi jebakan.